Senjakala Sekolah Kita
KONON, sekolah terbaik pada zaman halai-balai begini adalah yang termahal, lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya. Kian ekslusif maka semakin banyak dicari. Tak peduli kepala jadi kaki, dan kaki jadi kepala—apalagi cuma senyampang korupsi.
Intinya, anak harus sekolah. Orangtua bisa menangguk gengsi dari beban yang ditanggung anaknya.
Jika ditarik benang merah, antara penjara dan sekolah, ya setali tiga uang. Apalagi saat ini, sekolah sudah dengan sangat jeli menjadikan lembaganya sebagai sebuah industri.
Pendidikan anak-anak manusia sudah tak lagi penting. Pokoknya mereka lulus sebagai “sapi perah.”
Menyoal pendidikan anak-anak manusia, kita bisa melirik sejenak ke Finlandia. Negara yang katanya paling berhasil menjalankan fungsi pendidikan rakyat mereka di sekolah.
Pertanyaan kita, kenapa hanya sebiji saja negara di dunia ini yang punya kesadaran tersebut? Tak bisakah Indonesia seperti itu? Bisa, asal berani berpisah jalan dengan aturan dunia modern yang menggelikan. Kita ambil satu contoh saja.
Seorang saintis ahli vulkanologi sekali pun, tak mampu mendeteksi kapan sebuah gunung api meletus. Padahal mereka sudah sekolah setinggi mungkin sampai jenjang posdoktoral. Sementara Mbah Marijan (Raden Ngabehi Surakso Hargo) yang legendaris dan tak pernah mengenyam tetek-bengek pendidikan modern, berhasil meminta sahabatnya, Gunung Merapi, agar berkenan memberi kesempatan warga di sekitar, turun ke wilayah teraman—dan akhirnya meletus dengan dahsyat pada 2010 silam. Apa yang dilakukan Mbah Marijan tersebut adalah bukti jenis kecerdasan bahasa yang dimiliki manusia. Ya, kemampuan berkomunikasi dengan seluruh ciptaan Tuhan, dengan bahasa yang sama—bahasa kehidupan. Kita belum lagi membahas kecerdasan logis matematis yang dimiliki para juru taksir; kecerdasan ruang para pembuat sumur; kecerdasan waktu nelayan-petani yang membaca rasi bintang, atau mereka yang gemar menyintas; kecerdasan kinetik mereka yang menjadi pengolah tubuh macam Ip Man, Messi, dan Christiano Ronaldo; kecerdasan estetis kaum seniman; kecerdasan interpersonal kalangan pemimpin besar dunia; kecerdasan intrapersonal barisan intelijen negara; dan kecerdasan spiritual sekelompok manusia pembaharu zaman sekelas nabi, wali, lama, atau mpu.
Universitas hanya kamuflase

Sejak Paulo Freire (1921-1997) mengenalkan filsafat pendidikan pada masyarakat modern, tampaknya perubahan yang ia harapkan tak terlalu kentara di Dunia Ketiga. Negara berkembang kerap jadi bulan-bulanan Amerika dan anteknya di Eropa. Kolonialisme Abad ke-17 terus disalin rupa jadi liberalisme ekonomi. Kini kita mengenalnya dengan sebutan yang agak keren: pasar bebas! Anak kandung neo-liberalisme. Di titik inilah hulu petaka pendidikan kita. Sejak Mazhab Wina (eksakta) dan Frankfurt (humaniora) berebut gengsi pada permulaan Abad-20, sekolah tak lagi berdaya guna bagi para siswanya.
Universitas hanya sekadar kamuflase menjaring kelas pekerja. Selembar ijazah berikut torehan prestasi akademik yang mereka dapatkan, semata menjadi syarat untuk menghasilkan pundi-pundi kapital. Mahasiswa berpredikat summa cum laude dari fakultas eksak sekali pun, kadang bernasib lebih tragis tinimbang rekan seangkatan mereka, yang indeks prestasinya di bawah angka dua. Sebagian mahasiswa cerdas-jenius ini mati bunuh diri. Putus asa dengan dirinya yang jadi anomali di tengah masyarakat. Bahkan sudah jadi pemahaman umum, seorang sarjana tak tahu cara menerapkan ilmunya dalam kehidupan. Mereka kehilangan arah sedari dalam diri sendiri.
Anak-anak jenius yang dianggap gagal Cara kita menganggit pengetahuan hari ini, berbeda jauh dengan para pendahulu. Hidup yang serba mudah, membuat kita sulit memahami bahwa segala sesuatu ada awal dan tujuannya. Anak-anak manusia yang lahir, jelas membutuhkan bekal bagi hidup mereka. Tak semua kita bakal jadi pemimpin. Tak semua kita harus jadi insinyur. Tak semua. Hidup yang pusparagam begini, tak bisa didekati dengan pola dan pendekatan seragam. Sekolah, harusnya menggunakan pemahaman begini dalam proses belajar-mengajarnya. Anak-anak didik berperangai tak lazim, bisa serta-merta didepak dari sekolah lantaran dianggap mengganggu ketenangan belajar. Hanya segelintir pesantren misalnya, yang masih mau menerima santri paling nakal, onar, dan banyak polah, lantas mengarahkan bakat mereka sedemikian rupa. Sekian belas tahun kemudian, ternyata mereka sudah mendirikan pesantren dan jadi kiai yang disegani. Sekolah atau kampus yang gagal mengerti keunikan potensi manusia, baru menyadari kesalahannya beberapa tahun kemudian, pasca-menjatuhkan keputusan sepihak pada anak-anak jenius yang luar biasa sulit dikendalikan.
Einstein, Gus Dur, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg, adalah para teladan terbaik terkait anekdot kita ini. Pendidikan adalah harapan, perjuangan, dan perlawanan pada ketidaktahuan kita akan kondisi nyata kehidupan. Jika kita tahu apa yang sejatinya diketahui, maka hasilnya adalah pengetahuan. Belajar itu menembus batas. Bahkan tak berhenti sampai liang lahat. Semua kita tumbuh secara usia, kejiwaan, logika berpikir, keyakinan, dan spiritualitas. Pada puncak pencapaian itu, kita akan mengerti untuk apa semua ini diadakan Tuhan.
Cawan suci saintifik Kedigdayaan sains dan industri modern menghadirkan revolusi baru dalam hubungan manusia dengan alamnya. Saat Revolusi Agrikultur, umat manusia membungkam binatang dan tetumbuhan, lalu mengubah opera besar semesta jadi sebuah dialog antara manusia dan tuhan. Kala revolusi saintifik, umat manusia malah membungkam Tuhan juga. Dunia sekarang menjadi sebuah pentas tunggal manusia. Antroposen. Kita berdiri kesepian di panggung yang kosong, berbicara pada diri sendiri, lantas meraih kekuatan besar tanpa tanggung jawab apa pun. Setelah mengejawantahkan hukum bisu fisika, matematika, kimia, dan biologi, manusia kini memperlakukan semua di sekitarnya seenak jidat sendiri. Sebagai pewaris sah kehidupan kiwari, kita semua jelas menanggung beban yang sama besar. Baik Anda yang beragama atau tidak, pun yang ogah bertuhan.
Kehadiran kita yang serta-merta di planet biru ini menyimpan misteri agung yang perlu dijawab. Sekolah, jika tak segera menginsyafi kepandirannya, takkan mampu mengantarkan siswa-siswinya untuk menjawab kegelisahan primordial yang dibawa seluruh anak manusia sejak ia terlahir ke dunia. Menteri pendidikan Indonesia, para guru, dan juga dosen, harus pula menyadari betapa sejatinya, tak ada anak manusia yang bodoh. Grafik nilai bukanlah penentu jalan hidup seseorang. Kita hanya sedang berusaha menjawab begitu banyak ketidaktahuan, dengan pengetahuan baru—yang lucunya, melahirkan ketaksaan berikutnya. Ketahui dan sadarilah, wahai saudaraku, saat ini kita tengah melintasi sebuah era yang presedennya sedang dalam tahap perancangan. Keyakinan purba manusia yang terlembagakan dalam agama, sedang di ambang gelombang tsunami “Agama Data.” Pranata kehidupan kita akan berubah. Cepat atau lambat. IBM Watson, Deep Blue, AlphaGo, VITAL, OncoFinder, The Futurre of Employment, Annie, otomata selular, drone, adalah segelintir contoh upaya manusia zaman baru yang berusaha menguak tabir rahasia dari misteri kehidupan ini. Kecerdasan artifisial yang sudah mentas itu, terbukti berhasil melampaui pencapaian manusia Abad-21. Algoritma organik yang adalah kita, ternyata harus menelan pil pahit kekalahan atas temuannya sendiri. Sementara pada saat yang sama, sebagian besar manusia belum lagi terjaga dari tidur malamnya yang berkepanjangan di masa lalu.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Senjakala Sekolah Kita", Klik untuk baca: https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/06/17312101/senjakala-sekolah-kita?page=all#page2.
Editor : Heru Margianto



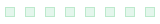

Komentar (0)